BAGIAN KE-1 (PERTAMA) DARI 3 TULISAN
Menjadi ‘lemot’ dan susah tidur.
Nikmat sehat memang lebih terasa saat kita sakit, saya menyadari penuh itu. Tetapi saya tidak pernah menyangka kalau ‘sakit’ terberat yang saya alami ini ternyata bukan sakit fisik, tetapi dicabutnya nikmat pikiran sehat.
Awalnya, usai melahirkan, saya merasakan penurunan fungsi kognisi yang sangat drastis. Belajar menggunakan pompa ASI, mengatur setelan car seat dan kereta bayi menjadi tugas berat karena saya harus membaca instruksi berkali-kali tetapi tidak kunjung mengerti. Saya pun bingung kenapa saya se’lemot’ ini. Memasak adalah salah satu kegiatan yang membuat saya frustasi kewalahan. Banyak resep yang dulu saya suka, sekarang tidak ingat lagi caranya. Untuk membaca instruksi pada resep pun harus berkali-kali karena susah sekali konsentrasi. Saya yang biasanya suka buka sosmed dan update perkembangan berita di dalam dan luar negeri, jadi kudet kalau diajak ngobrol karena memang tidak pernah lagi ngikutin berita. Membaca literatur tentang menyusui pun butuh waktu yang lama. Grup-grup Whatsapp yang biasanya menemani, cuma di clear chat sampai akhirnya keluar. Bahkan hal simpel seperti memilih dan memesan popok di Amazon bisa membuat otak saya kewalahan, overwhelmed, linglung. Saya juga membutuhkan waktu yang lama untuk bersiap-siap keluar rumah serta menyiapkan perlengkapan bayi untuk bepergian. Segala ‘cita-cita ambisius’ seperti mengajak bayi traveling harus saya pupus dalam-dalam. Gimana mau packing dan traveling kalo cuma keluar rumah aja linglung?
Semua itu menyebabkan saya frustasi dan cemas berlebihan: Kenapa saya jadi lemot begini? Bagaimana saya bisa jadi ibu yang baik kalau mikir aja lama? Perasaan itu berkembang menjadi rasa bersalah dan rendah diri berlebihan. Belakangan saya baru tahu dari psikiater di unit gawat darurat kalau apa yang saya alami namanya pseudo dementia. Sulit konsentrasi, mudah lupa, kesulitan dan kurang minat melakukan hal-hal yang dulu biasa dilakukan, jadi linglung dan lemot itu hanyalah salah satu gejala yang biasanya menyertai depresi.
Gejala lainnya adalah susah tidur atau insomnia. Awalnya, saya beranggapan wajar sekali kalau punya bayi kurang tidur. Pada usia 1.5 bulan, perut Keeva bermasalah dan kerap menangis. Dokter menyuruh saya diet agar ASI saya tidak bergas. Ia juga memberi Keeva obat pereda kolik dan GERD karena ia susah tidur telentang dan terus bangun menangis. Kadang saya menidurkannya di car seat karena dia tidak kunjung tidur dalam posisi telentang dan harus selalu digendong. Memang benar, kurang tidur buat ibu yang baru bersalin itu wajar. Tetapi, tidak bisa tidur sama sekali selama 24 jam bahkan lebih, adalah di luar kewajaran dan dapat memicu psikosis, yaitu keadaan mental yang terganggu dimana penderita kehilangan kontak dengan realita/kenyataan. Bisa mengalami delusi (percaya suatu hal yang bukan kenyataan), halusinasi (mendengar atau melihat hal yang tidak nyata) atau keduanya. Inilah yang saya alami. Psikosis pasca melahirkan/postpartum psychosis adalah gangguan mental pasca melahirkan yang paling berat dan masih tergolong jarang. Baby blues adalah gangguan ringan, lanjutannya adalah depresi pasca melahirkan/postpartum depression (PPD). Banyak wanita pasca melahirkan mengalami depresi, tapi kebanyakan tidak disertai psikosis. Sebaliknya psikosis pasca melahirkan biasanya selalu disertai depresi. Karena inilah akhirnya saya harus berpisah dengan Keeva ketika usianya hampir 4 bulan. Saya harus dirawat di unit kesehatan mental di rumah sakit.
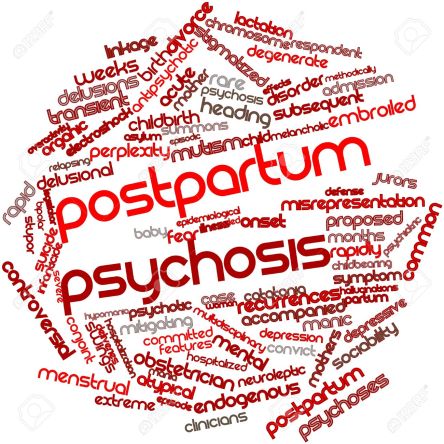
Yang lebih mengejutkan buat saya adalah semua ini terjadi setelah kehamilan yang menyenangkan dan proses persalinan yang sangat mudah. Pada saat hamil, saya hepi banget, jauh dari depresi. Kehamilan dan janin juga sehat serta lolos segala macam test yang seabgreg-abreg buat perempuan hamil di atas 40 tahun. Saya sangat semangat mengatur menu sehat, menjaga benar apa yang saya makan, berolahraga renang setiap hari, bersepeda ke kantor sampai usia kehamilan 6 bulan, tetap aktif dan bekerja sampai minggu terakhir kehamilan. Semua saya lakukan karena saya bertekad punya anak sehat dan melahirkan secara normal. Alhamdulillah, persalinan saya sangat mudah dan tidak sesakit yang saya bayangkan. Setelah berenang di siang hari, sore sampai malam saya terus berkontraksi dan dini hari saya melahirkan. Dokter Kandungan (Obgyn) saya pun selalu mendukung dan memberi semangat untuk bisa melahirkan normal. Ia membuat saya lebih pede walau tadinya cemas karena pernah keguguran dan kini mengandung di usia 40 tahun. Kehamilan yang bermasalah dan komplikasi saat melahirkan bisa merupakan faktor pemicu depresi pasca melahirkan. Tetapi belajar dari kasus saya, ternyata ibu-ibu yang hamilnya sehat dan lahirannya gampang pun harus tetap waspada dengan depresi pasca melahirkan.
Menolak minum obat anti depresi
Saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika setelah usia Keeva lewat 2 bulan, saat ia akhirnya bisa tidur nyenyak semalaman tanpa bangun, saya masih tetap tidak bisa tidur. Malam hari saya malah gelisah dan beberes rumah, merapikan dokumen, sampai memperbaiki thermostat AC. Kalau diam di tempat tidur pikiran terus berkecamuk sehingga saya harus mengalihkannya dengan melakukan sesuatu. Saya mencoba minum obat tidur dijual bebas yang diperbolehkan untuk ibu menyusui (Diphenhydramine HCl). Efeknya hanya tubuh saya yang lelah, seperti paralyzed, kaku tidak bisa bergerak dari tempat tidur tetapi pikiran tetap berkecamuk, segala macam kekhawatiran seolah berlomba-lomba di otak saya dan tidak bisa distop. Belakangan saya baru tahu dalam istilah psikiatri kalau ini namanya racing thoughts, alias pikiran yang berkejaran. Ternyata ini juga gejala dari psikosis pasca melahirkan.
Melihat kondisi saya yang paralyzed di tempat tidur, suami saya pun baru mengerti saya mungkin mengalami depresi. Saat itu suami baru bercerita bahwa dokter anak saya sudah melihat gejala depresi pasca melahirkan saat kunjungan 2 bulan Keeva, karena saya tampak khawatir berlebihan. Saat saya ke toilet, ia menanyakan pada suami apakah saya terlihat depresi, pernah kelihatan menyakiti bayi, atau diri sendiri? Apakah perlu diresepkan obat penenang? Saat itu suami saya tentu saja menjawab tidak. Kini ia melihat sendiri walau saya tidak pernah menyakiti bayi atau diri sendiri, saya kelihatannya butuh obat resep dokter. Sayangnya saya masih bersikeras tidak mau minum obat. Sebagai orang yang jarang sakit, menjaga tidak sampai sakit dan tidak mau minum obat kalau tidak perlu-perlu banget, saya ngeri berurusan dengan obat penenang. Saya masih bandel dan gengsian dan beranggapan ini akan sembuh sendiri. Saya baru ‘menyerah’ ketika suatu malam saya bukan hanya tidak bisa tidur dan racing thoughts mengganggu lagi, tapi kali ini saya merasa otak seperti ‘disengat listrik’ dan merasa ada yang mem’bajak’ pikiran saya sehingga saya mendadak bukan diri saya. Paginya, suami membawa ke dokter Obgyn saya. Saat itu saya merasa bersalah karena merasa penyakit saya ini “nggak penting”, si dokter pasti punya kerjaan lainnya yang lebih penting daripada melayani seorang yang “cuma depresi”. Saya menganggap diri saya lemah dan cengeng. Di situlah dokter mengatakan bahwa rasa bersalah yang berlebihan juga ciri depresi. Ia berulang kali mengatakan: “Jangan merasa malu, jangan merasa bersalah. Siapapun bisa kena depresi. Sama saja dengan orang yang sakit diabetes atau darah tinggi, mereka harus minum obat. Depresi kamu terjadi karena ketidak seimbangan senyawa kimia di otak, juga pengaruh hormon-hormon pasca melahirkan, sehingga kamu perlu obat untuk menyeimbangkannya atau terapi hormon.” Setelah dibujuk akhirnya saya mau juga minum obat anti depresi. Saya masih ingin menyusui, karena itu obat anti depresi yang dipilih pun untuk yang masih aman bagi ibu menyusui, yakni Setraline HCl (Zoloft). Sang dokter tetap menyarankan saya ke psikiater, karena dari gejala yang saya tuturkan, ia berkata saya mungkin tidak hanya terkena depresi pasca melahirkan tetapi juga psikosis pasca melahirkan, dan psikiater lah yang bisa menindak lanjuti obat apa yang paling cocok.
3 hari setelah meminum obat anti depresi, saya merasa kondisi saya bertambah lemah dan semakin parah. Perut sakit luar biasa, otot tremor sehingga sulit untuk beraktivitas, insomnia malah menjadi-jadi. Kalaupun bisa tidur sekilas, isinya mimpi buruk semua. Pagi hari yang harusnya saya semangat mengasuh Keeva, malah lebih tidak bertenaga sama sekali. Saya semakin takut tidak bisa menunaikan tugas sebagai ibu, kasian si bayi sendirian di rumah dengan ibu yang ‘sakit’. Ayah mertua adalah seorang pharmacist (apoteker), menurut beliau, semua obat anti depresi tidak langsung cespleng mujarab, tetapi malah biasanya “getting worse before getting better”. Jadi kondisi saya yang bertambah buruk sebelum merasakan efek membaik adalah lumrah. Saya diminta sabar selama 2-4 mingguan, sampai obatnya bekerja. Saya malah semakin takut. Apa? Saya harus menunggu selama 4 minggu? Selama 4 minggu mengasuh anak sendirian dengan kondisi seperti ini? Kalau di Jakarta mungkin masih bisa, karena ada yang membantu. Bagaimana kualitas pengasuhannya nanti kalau Keeva diasuh oleh ibu yang di bawah pengaruh obat? 4 minggu, terlalu banyak perkembangan Keeva yang tidak bisa saya ikuti optimal. Karena tidak tahan lagi dengan efek samping obat yang malah membuat saya makin tidak bisa menjalankan fungsi sebagai ibu, saya melaporkan ke dokter. Saya diperbolehkan untuk menghentikan obat pada hari ke-4, sebelum terlalu jauh yang berakibat lebih parah jika mendadak dihentikan. Kondisi saya memang sejenak membaik dan saya bisa lebih ‘menikmati’ mengasuh Keeva. Dokter Obgyn tetap bersikeras saya harus ke psikiater, untuk menemukan obat yang cocok dan efek sampingnya tidak begitu parah.
Masuk unit gawat darurat psikiatri
Ternyata memilih psikiater dan menjadwalkan kunjungan pada akhir tahun saat liburan Natal dan Tahun Baru tidak mudah, apalagi saat itu saya sedang dalam proses pergantian dari asuransi kesehatan yang lama ke yang baru. Proses administrasi yang ribet membuat saya dan suami sama-sama lalai dan setelah pergantian ke tahun 2017 kami belum juga membuat janji dengan psikiater. Kondisi saya makin memburuk. Hari-hari dimana saya masih bisa berfikir jernih, makin sedikit jumlahnya dibanding dalam keadaan ‘linglung’. Merawat Keeva sebatas mengganti popok dan menyusui saja, saya makin tidak merasakan ikatan batin dengannya. Tidak ada emosi dan energi untuk mengajaknya bermain, menyanyikan lagu atau membacakan buku. Suatu hari saya keluar rumah dan meninggalkan Keeva tidur sendirian karena ‘sengatan listrik’ itu datang lagi dan saya merasa linglung berat. Malam-malam saat Keeva dan suami tidur, saya bukannya tidur, malah mencakar-cakar lengan sendiri. Saya menelpon kakak saya di Jakarta memintanya datang ke Dallas, menyelamatkan Keeva dari ibunya yang ‘gila’, saya paranoid bahwa Child Protection Service akan mengambil Keeva karena saya dan suami tidak mampu mengurusnya. Paranoid bertambah parah saat saya merasa semua orang di seluruh dunia yang saya kenal membenci saya, ngomongin saya dan menertawakan saya atas ketidakkompetenan saya merawat Keeva. Puncaknya ketika saya di kantor dan pulang sebelum waktunya karena merasa saya telah dipecat. Atasan saya datang ke apartemen kami untuk menjelaskan bahwa itu tidak benar. Sepulangnya dia dari apartemen, suami makin khawatir karena saya semakin kehilangan kontak dengan realita, tatapan saya kosong, saya merasa saya tidak berguna, Keeva butuh ibu yang lebih baik dari saya. Saya mulai menyakiti diri sendiri dengan mencubit dan menampar pipi saya sendiri. Suamipun membawa saya ke unit gawat darurat, jelas tidak mungkin dengan kondisi ini saya sendirian di rumah merawat Keeva. Paranoid dan menyakiti diri sendiri atau bayi juga merupakan gejala psikosis. ‘Untungnya’ saya ‘hanya’ menyakiti diri sendiri bukan Keeva.
Setelah mendatangi unit gawat darurat, saya menjalani MRI dan berbagai tes lainnya sampai hampir malam hari. Suami harus pulang karena Keeva harus minum susu dan tidur. Sepeninggal suami, saya ditransfer ke dalam fasilitas kesehatan mental di Medical City Dallas. Sesuatu yang sangat tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Keeva dititipkan kepada ibu mertua yang cuti dari kerjanya untuk mengasuh sang cucu.
Apop hebat Dan kuat. Alhamdulillah masa itu sudah terlewati yaaa…..Aku juga sempat “jet lag” dgn kehamilannya yg terakhir…dgn usia sudah 40 tahun Dan prahara rumah tangga selama kehamilan Qya, belum lagi berjuang menghadapi thesis yg harus selesai… alhamdulillah semua bisa terlewati. Being a single mom in Qya’s life….semua dinikmati Karena taking Allah gak Akan meninggalkan Kita.
Tetep semangat yaaa Apop…Allah bless you and Keeva always…aameen
Haduh gak kebayang ya single mom dengan thesis pulak. Makasih ya Martio
Teteh👍👍👍
Alhamdulillah
Ga sabar nunggu lanjutan ceritanya
🙂
apop…I am touched and feel you. Semangat ya, Pop….God bless you
Thanks Angel
Jalani prosesnya ya Pop. Tuhan pasti menjaga semua dan memulihkan dirimu. Kita ikut doakan. Sangat menginspirasi ceritamu. Bagikan bebanmu pada kami temen temenmu .. Mudah mudahan bisa beri semangat walau fari jauh
Makasih banyak Cinthia
Apop, I’m so sorry… I should have given you a call more frequently. I never thought you experienced this. Kudos for you. You are such a strong woman.
Dedeeek gak papa Dek alhamdulillah sekarang udah baik-baik aja
Pingback: Ketika Nikmat ‘Waras’ itu Dicabut: Pengalaman Melawan Psikosis dan Depresi Pasca Melahirkan (3) | marthiany
alhamdulillah..blogwalking ttg depresi nyasar disini..nice share mba..sangat bermanfaat..jd nambah ilmu baru..semoga tetep sehat y mba..salam kenal 🙂
Pingback: Bunuh Diri, Rahman dan Rahim | marthiany
Mba, terima kasih banyak sudah membagikan cerita ini. Moga kita semua fit selalu, jiwa & raga. PPD itu nyata.
Pingback: Berbeda-beda tetapi Tetap Texas | marthiany
Tan saya boleh minta kontaknya? Saya butuh informasi sekali
bisa message di Facebook Messenger, FB saya Apop Harris
👍👍👍❤❤❤terimakasih banyak mba apop cerita ya…sangat menarik,sy jadi belajar dari cerita tersebut….
Sama-sama mbaak…nuhun sudah mampir