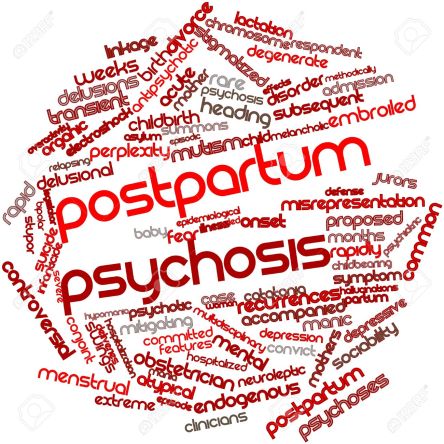BAGIAN KE-3 (TERAKHIR ) DARI 3 TULISAN
Berjuang melawan efek samping obat.
Berikut ini saya terjemahkan peringatan yang tercantum dalam leaflet obat anti depresi yang saya konsumsi, Fluoxetine (Prozac):
“Tablet Fluoxetine dan obat anti depresi lainnya dapat menyebabkan efek samping serius, termasuk dapat meningkatkan keinginan dan tindakan bunuh diri dalam beberapa bulan pertama atau ketika dosis dinaikkan”.
Terdengar aneh? Buat saya yang awam, iya. Kenapa obat anti depresi malah bisa meningkatkan pikiran dan tindakan bunuh diri? Rupanya awal pemberian obat anti depresi memang dapat menimbulkan apa yang disebut ‘jitteriness syndrome‘: cemas, gelisah, susah duduk diam, sehingga bisa memicu pikiran dan tindakan nekat. Ini yang disebut ayah mertua saya dalam bagian pertama tulisan ini sebagai “getting worse before getting better”. Gejala akan bertambah parah sebelum obatnya mulai menunjukkan hasil. Di sinilah kesabaran keluarga yang mendampingi saya diuji.
Sepulang dari rumah sakit, saya dan Keeva tinggal di rumah mertua, suami tetap tinggal di apartemen. Saya bahagia saat akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Keeva, tetapi ikatan emosi padanya belum sepenuhnya pulih. Malam hari saya merasa lebih baik dia tidur dengan ibu mertua supaya saya bisa beristirahat. Alhamdulillah, buat ibu mertua, cuti menjaga Keeva merupakan refreshing dari kerjanya dan ia sangat menikmatinya. Energinya sangat positif, walau ia bukan muslim ia kerap mengingatkan saya untuk tetap sholat. Saat itu kemajuan yang saya rasakan adalah bisa tidur nyenyak. Tetapi kecemasan saya bertambah, terkadang mondar-mandir tidak bisa diam. Mandi dan berpakaian seperti tugas berat, karena saya gelisah melihat pakaian kotor. Saya membuat ibu mertua khawatir dengan jungkir balik di kasur dan meracau bahwa saya tidak pantas ditolong. “Kalau mau tolong Keeva, tolonglah Keeva. Biarkan saja saya”. Pada waktu itu saya juga tidak mengerti mengapa saya bersikap seperti itu. Ayah mertua saya yang pharmacist nampaknya sudah paham bahwa ini efek samping obat, ia bertanya kapan saya menemui kembali psikiater? “Kemungkinan nanti dosis kamu ditambah atau obatnya diganti.” katanya.
Satu lagi, saya terkadang seperti tidak merasakan sedih atau senang. Datar saja tanpa emosi. Ketika kakak saya, Ades, membawa kabar gembira bahwa visa kunjungannya disetujui, ibu mertua saya dan suami yang peluk-pelukan bahagia. Saya malah datar saja. Saat Ades minta saya menulis daftar apa saja yang mau dibawakan dari Jakarta, saya malah tidak kepingin apa-apa. Padahal perjuangan Ades dimulai dari membuat e-paspor sampai harus antri berhari-hari, baru berhasil pada hari ke-5 dimana akhirnya mengantri dari jam 2 pagi. Kemungkinan diterimanya juga belum jelas. Ketika itu Donald Trump baru terpilih dan Indonesia termasuk dalam watch list negara yang dibatasi jumlah visa kunjungannya. Di luar itu, untuk mendadak pergi dari Jakarta, sebenarnya Ades pun harus meninggalkan sejumlah urusan penting yang belum tuntas.
Hari yang dinanti itu tiba. Saya, suami dan Keeva menjemput Ades dari bandara. Saat di parkiran, perasaan tidak enak itu muncul lagi. Saya ingin lari keluar dari mobil dan tidak bisa duduk diam. Suami bukan main khawatirnya. Apalagi saat itu ia dan Keeva tinggal di mobil dan saya sendiri yang mencari Ades di bandara. Saat berlari dari satu terminal ke terminal lainnya mencari Ades, saya merasa menjadi diri saya sendiri. Akhirnya saat saya melihat Ades, saya segera memeluknya sambil menangis. Ya, saya bisa menangis! Setelah sekian lama saya merasa tanpa emosi, saya gembira sekali akhirnya bisa mengeluarkan air mata.
My sister, my hero.
Setelah kakak saya Ades datang, saya dan Keeva kembali tinggal bersama suami di apartemen. Kalau ada penghargaan orang paling keras kepala dan pantang menyerah sekaligus selfless berkorban untuk kepentingan orang lain, mungkin saya akan menganugerahkannya pada Ades. Ialah yang harus menghadapi hari-hari awal di mana efek obat saya “getting worse before getting better”. Bagaimana tidak, saat ia datang membawakan oleh-oleh dari keluarga dan teman-teman di Jakarta, saya bukannya bergembira dan berterima kasih, malah super cemas karena tidak tahu mau disimpan di mana oleh-oleh sebanyak itu. Saya juga panik melihat tumpukan baju kotor darinya. Ada banyak kecemasan-kecemasan kecil terhadap hal-hal yang sebelumnya sama sekali bukan masalah bagi saya. Ini juga merupakan karakteristik depresi. Saat ia baru datang dan masih jetlag, saya malah meninggalkannya tidur bersama Keeva. Saya keluar dan memandang jembatan jalan layang dan berpikir untuk menjatuhkan diri dari jembatan. Kira-kira kalo jatuh langsung mati nggak ya?, kurang tinggi nggak ya jembatannya, pikir saya waktu itu berkalkulasi. Untung suami menelpon saya karena Ades memberitahunya. Akhirnya saya balik lagi ke apartemen. Kebayang paniknya Ades saat bangun tidur siang, karena saya tidak ada di apartemen, dan dia baru saja datang sehingga tidak tahu harus mencari kemana. Yang paling horror tentu saja saat ia menemukan saya di kamar, dengan kabel listrik dari lampu tidur terjerat di leher saya. Satu lagi, ia juga memergoki saya mengambil pistol suami. Sebelum minum obat ini, saya hanya merasakan pikiran bahwa Keeva lebih baik tanpa ibunya, saya benci diri saya, mendingan saya meninggalkan Keeva. Tetapi tidak sampai memikirkan metode, apalagi melakukan tindakan. 3 kali Ades menyelamatkan saya dari tindakan bodoh itu. Kalau tidak ada dia mungkin Keeva sudah tidak punya ibu. Banyak sekali ‘dosa’ saya sama Ades, saya cuma berharap Tuhan mengampuni karena saya masih ‘sakit’. Yang ada di pikiran saya waktu itu: Sekarang sudah ada Ades, biarlah Ades yang merawat Keeva, dia lebih telaten, dia lebih berhak punya anak daripada saya. Biarlah saya pergi saja. Twisted banget kan? Berbagai upaya diusahakan kakak dan suami untuk meluruskan twisted mind ini. “Terus, kalo mati, ntar Ades dong yang repot bawa mayatnya ke Jakarta? Harus bilang apa sama mama papa?”. Suami sampai mengancam “Kalau kamu bunuh diri saya akan bilang Keeva bahwa ibunya melakukan itu karena benci pada anaknya”. Kami jadi cukup sering terlibat dalam pembicaraan yang penuh dengan muatan emosi naik turun. Melelahkan untuk semua.
Kalau ingat sekarang rasanya malu, tetapi saya rasa episode ini penting diceritakan untuk menunjukkan bahwa pendampingan sangat diperlukan dalam tahap awal konsumsi obat anti depresi. Kita tidak pernah tahu seburuk apa efek getting worse itu pada tiap pasien.
Selain pikiran saya yang masih kacau, saya juga menderita sakit fisik di tangan hingga dalam posisi tertentu tidak bisa mengangkat Keeva. Seperti ada kejutan listrik di kedua pergelangan tangan. Dokter umum di Dallas mendiagnosa bahwa ini Carpal Tunnel Syndrome biasa, ia memberikan obat anti peradangan dan menyuruh saya membebat tangan saya dengan splint. Tapi sampai beberapa bulan tidak kunjung membaik, malah bertambah nyeri. Belakangan dokter bedah tulang di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta-lah yang memberikan diagnosa dan tindakan yang lebih tepat. Namanya De Quervain syndrome, atau mommy thumb. Rupanya si dokter sendiri pernah mengalaminya sampai harus dioperasi. Sering terjadi pada ibu baru melahirkan karena terlalu sering mengangkat bayi, dan umumnya terjadi setelah 3 bulan melahirkan saat berat bayi sudah mulai meningkat. Faktor usia saya yang sudah 40, bertubuh kecil dengan bayi yang besarnya di atas rata-rata juga memperbesar resiko. Saya datang pada saat yang tepat, saya hanya di suntik steroid di tendon pergelangan tangan. Untunglah, kata dokter, telat sedikit saya mungkin harus dioperasi.
Dengan keadaan yang sulit mengangkat Keeva pada saat itu, tentu saja keberadaan kakak saya sangat berarti. Kehadirannya bukan hanya membantu saya dalam merawat Keeva, tetapi juga menyadarkan kembali saya akan pentingnya bentuk-bentuk ikhtiar lainnya untuk mencapai kesembuhan, selain minum obat. Ia menunjukkan video di YouTube tentang berbagai macam kasus depresi dan psikosis pasca melahirkan, seperti seorang perempuan terkena delusi aneh sampai yakin bahwa bayinya sudah mati. Ia menunjukkan keadaan perempuan itu sekarang baik-baik saja dan anaknya sehat, meyakinkan bahwa saya juga bisa sembuh seperti dia. Ades juga merukyah saya, mengajak saya yoga, membawakan buku-buku doa, air zam-zam dari temannya, mencoba menghubungkan kembali saya dengan teman-teman Indonesia di Dallas, bahkan membuatkan minuman kunyit setiap hari.
Kenapa kunyit? Ternyata dari jurnal ilmiah yang ia baca, kunyit sudah dicobakan pada penderita depresi. Terbukti bahwa gabungan kunyit + fluoxetine yang saya minum memberikan efek lebih baik sebagai anti depresi, daripada hanya minum fluoxetine saja. Kunyit juga mengaktifkan gen yang memproduksi antioksidan, membantu organ hati mengeluarkan racun dan menghambat peradangan yang menyebabkan fungsi otak terganggu. Sebagaimana kita ketahui, depresi terjadi karena ketidakseimbangan senyawa kimia di otak. Dengan khasiat anti peradangan itulah kunyit membantu meningkatkan kemampuan regenerasi sel otak, menaikkan kemampuan otak meregulasi hormon dan memproduksi serotonin, senyawa yang dibutuhkan untuk menanggulangi depresi. Mungkin inikah salah satu sebabnya perempuan Indonesia jaman dulu lebih jarang terkena depresi? Mereka rajin minum jamu usai melahirkan, juga banyak menggunakan kunyit pada bumbu makanan sehari-hari, selain tentu saja sinar matahari yang berlimpah dan tradisi yang jarang membiarkan ibu baru melahirkan mengasuh bayinya sendirian.

Ades dan Keeva, Maret 2017, di apartemen kami.
Dosis dan jenis obat ditambah.
Pada kunjungan psikiater rawat jalan yang pertama kali setelah saya keluar dari rumah sakit, saya menceritakan semua percobaan bunuh diri yang saya lakukan dan bagaimana saya malah merasakan cemas dan gelisah yang bertambah.
Dari situ diagnosa terakhir saya adalah “Major Depressive Disorder, severe with Psychotic Features”, depresi saya sudah mencapai taraf ‘severe’ alias parah. Artinya pengobatan tidak atau belum menunjukkan respon positif. Dokter mengajukan 2 alternatif: 1. Meningkatkan dosis obat, 2. Mencoba electroconvulsive therapy, yaitu menyetrum otak dengan arus listrik saat pasien dalam keadaan bius total. Terapi ini harus dilakukan 3 minggu sekali dan efek samping yang mungkin terjadi adalah kebingungan dan kehilangan ingatan terhadap hal-hal yang terjadi sebelum terapi. Dari situ suami dan saya memilih untuk meningkatkan dosis obat, karena secara waktu terasa lebih mungkin dilakukan, lagipula ngeri membayangkan memory loss akibat kejutan listrik.
Selain meningkatkan dosis obat, dokter menambahkan lagi satu obat, lorazepam, sebagai penenang jika diperlukan. Fungsinya untuk mengcounter efek samping awal dari fluoxetine yang menyebabkan jitteriness syndrome yang saya alami. Saya pikir: duh, repot banget ya, efek samping obat A musti dicounter dengan obat B, nanti obat B ada lagi efek sampingnya dan harus minum obat C. Sungguh rumit, inilah makanya saya dari dulu menghindari minum obat.
Untungnya, lorazepam ternyata cocok buat saya. Efeknya langsung terasa beberapa saat setelah meminumnya. Saya merasa optimis dan seperti bisa menjadi diri sendiri lagi. Menurut Ades, obat itu digunakan kriminal untuk merampok bank, supaya bisa tenang dan menghilangkan cemas dalam menjalankan misinya. Dengan bantuan obat ini, banyak kemajuan yang bisa dicapai sehingga saya mulai pede keluar dan mengajak Ades jalan-jalan keliling Dallas. Kami pergi ke museum-museum dan taman-taman di Dallas. Ades juga saya kenalkan dengan beberapa rekan kerja saya, salah satunya Harianne, seorang ibu berusia 70 tahun. Ia suka membawakan saya makanan dan menemani saya di apartemen saat kondisi saya kritis dan merasa tidak bisa menjalani hari sendiri. Saya selalu membawa lorazepam untuk berjaga-jaga. Saat kami pergi ke kedai kopi, di perjalanan saya merasa jitteriness syndrome muncul lagi sehingga terpaksa mengkonsumsi lorazepam. Hasilnya setengah jam kemudian saya merasa enak. Saat itu saya bahkan berkata pada Ades, “Seandainya harus minum obat ini seumur hidup, rela aja deh, yang penting bisa menikmati mengasuh Keeva”. Kebayang nggak, pernyataan ini muncul dari seorang yang dulu paling ogah minum obat. Perasaan saya antara senang bisa berfungsi dengan normal, tapi juga takut kecanduan. Kadang saya paksakan tidak meminumnya sampai saya merasa benar-benar tidak mampu. Saya tidak ingin nantinya ketergantungan obat.
Berhubungan kembali dengan keluarga dan teman-teman.
Ades kemudian menceritakan rencananya mengajak saya ke Houston bertemu temannya untuk refreshing dan melakukan rukyah dengan seorang Ustadz kenalan teman tersebut, sekalian untuk latihan bepergian naik pesawat dengan membawa Keeva. Ia bertekad membawa saya pulang ke Jakarta menemui keluarga. Katanya, kalau perjalanan udara yang dekat ke Houston (1 jam) bisa saya dan Keeva lalui, kita bisa lanjut ke perjalanan jauh ke Jakarta. Mulanya saya menganggap rencana Ades membawa saya ke Jakarta masih terlalu ambisius, tetapi ternyata kondisi saya terus membaik dan saya mulai merasa pede untuk bepergian.
Berkat Ades akhirnya Keeva bisa naik pesawat pertama kali ke Houston. Sedikit-demi sedikit, kemampuan kognisi saya mulai pulih, dan paranoid saya mulai menghilang. Saya mampu browsing internet untuk mencari cara membuat paspor anak, dan pergi sendiri ke kantor layanan publik mengurus akte kelahiran untuk paspor Keeva, tanpa mengalami kelelahan mental yang berlebihan.
Alhamdulillah, keadaan saya makin membaik dan akhirnya pelan-pelan saya mampu packing untuk perjalanan jauh ke Jakarta. Keeva ternyata bayi yang sangat gampang, sama sekali tidak menyusahkan dalam perjalanan 26 jam dari Dallas – Dubai – Jakarta. Malah saya yang menyusahkan, karena waktu itu saya tidak meminum lorazepam. Padahal ini merupakan perjalanan panjang dan berat. Walhasil saya sama sekali tak bisa tertidur dan banyak memarah-marahi Ades. Ketika akhirnya saya sadar, saya sangat menyesal. Saya bertanya,”Kenapa Ades baik dan sabar banget sih?” Jawabannya amat menohok, “Karena cuma dengan jadi orang baik Ades bisa berkumpul di surga dengan anak Ades nanti”. Oh ya, saat kondisi lelah tanpa tidur ini Ades putuskan untuk membuka kamar di hotel transit di bandara Dubai. Ia meminta saya untuk mencoba istirahat dan tidur. Di sini pentingnya pendampingan saat dalam terapi, karena seringkali saya tidak bisa berpikir jernih dan kurang bisa membuat keputusan yang akurat terhadap hal-hal yang dihadapi.
Kedatangan Keeva di Jakarta sangat menyenangkan orang tua dan keluarga saya, disusul kunjungan saudara dan teman-teman saya ke rumah kami di Pondok Kelapa yang ingin melihat Keeva. Keeva seolah-olah menjadi perantara yang memungkinkan kembali saya bertemu kembali teman-teman SMP, SMA, kuliah dan kantor yang sudah lama tidak bersua. Suasananya betul-betul seperti lebaran. Kami menghabiskan waktu sebulan di Jakarta, sebelum akhirnya Ades mengantar saya dan Keeva kembali ke Dallas.
Sepulangnya dari Jakarta, saya mulai berhubungan lagi dengan orang-orang Indonesia di Dallas, pergi ke rumah sahabat saya Leyla untuk makan-makanan Indonesia bareng-bareng. Leyla adalah orang yang pertama tahu bahwa saya masuk rumah sakit, dari suami saya. Suami ketika menyadari saya seperti bukan diri saya, ia menghubungi Leyla untuk menanyakan apakah Leyla merasakan hal yang sama. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Tetapi Leyla diwanti-wanti oleh suami untuk tidak memberitahu siapa-siapa, karena ingin menjaga privacy saya. Saat itu saya masih paranoid, mencurigai Leyla sebagai salah satu teman yang ngomongin dan menertawakan saya. Setelah kejadian ini sayapun baru tahu, saat itu Leyla merasa dilema antara ingin memberitahu teman-teman lain di Dallas untuk membantu, tetapi juga tidak ingin ikut campur. Di sini saya juga telat menyadari pentingnya mengakui kalau kita punya masalah dan butuh pertolongan. Saat keluarga kita jauh di sana, teman-teman dekat kitalah yang bisa menjadi keluarga kita di sini.
Penutup.
Saat saya menulis ini, keadaan saya sudah jauh membaik, bisa dibilang 95%. Saya masih harus mengunjungi psikiater 4 bulan sekali. Dari 4 jenis obat yang saya minum di awal, sekarang hanya tinggal 1 saja, dan psikiater baru akan mengurangi dosisnya bulan Januari 2018 nanti, untuk kemudian distop sama sekali.
Usia Keeva sekarang 14 bulan, ia senang sekali bermain dengan tupai, burung, bebek dan anjing. Ia sudah bisa berjalan dan membantu mamanya menaruh cucian piring bersih: